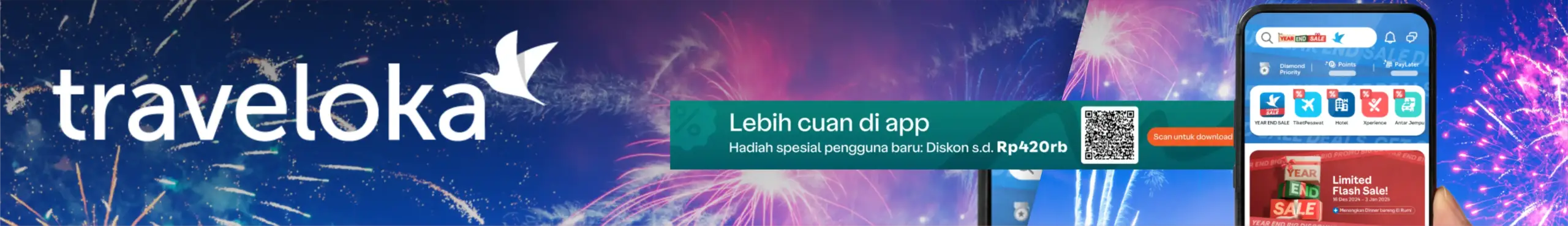Magetan, Berita Nusantara 89. Peristiwa yang terkenal sebagai Gerakan 30 September (G30S PKI) tetap menjadi salah satu bab kelam dalam sejarah Indonesia. Dini hari 1 Oktober 1965, sekelompok militer yang menyebut diri G30S melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah jenderal Angkatan Darat. Para jenderal yang menjadi korban antara lain Jenderal Ahmad Yani, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen R. Soeprapto, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo.
Sementara itu, Jenderal A.H. Nasution berhasil lolos dari penculikan. Sayangnya ajudan beliau Letnan Satu Pierre Tendean menjadi korban penculikan. Tragedi ini juga ikut menewaskan putri bungsunya, Ade Irma Suryani, yang tertembak oleh pasukan yang menyerbu kediamannya. Selain itu, peristiwa ini juga menewaskan Brigadir Karel Sadsuitubun yang saat itu sedang menjaga rumah Wakil Perdana Menteri J. Leimena yang berada di sebelah kediaman Nasution.
Kelompok G30S juga menguasai fasilitas strategis seperti markas Radio Republik Indonesia (RRI), dari mana mereka menyiarkan pernyataan bahwa Dewan Jenderal hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno, dan mengklaim bahwa mereka bertindak demi “penyelamatan negara”. Selanjutnya di Jawa Tengah atas nama Gerakan 30 September, Wali kota PKI Solo, Utomo Ramelan, mengeluarkan pernyataan mendukung gerakan tersebut. Di Yogyakarta, Mayor Muljono memimpin pemberontakan, menculik dan kemudian membunuh Kolonel Katamso dan kepala stafnya Letkol Sugiyono.
Namun, begitu berita kegagalan G-30-S di Jakarta, sebagian besar pengikutnya di Jawa Tengah menyerah. Pada tanggal 5 Oktober, Katamso dan Sugiyono, komandan dan pejabat eksekutif Daerah Militer ke-72 pada saat pembunuhan mereka, juga secara anumerta mendapat gelar sebagai Pahlawan Revolusi.
Latar Belakang yang Memicu G30S/PKI
Di awal dekade 1960-an, Indonesia menghadapi berbagai ketidakstabilan, ekonomi memprihatinkan, konflik ideologi, dan ketegangan politik antar kekuatan. Presiden Soekarno berupaya meredam konflik melalui gagasan Nasakom—memadukan nasionalisme, agama, dan komunisme—namun ketegangan antara PKI dan militer tetap mengemuka. PKI tumbuh menjadi kekuatan besar, dengan anggota yang mencapai jutaan dan pengaruh di organisasi massa dan petani. Di sisi lain, militer—khususnya Angkatan Darat—mulai meresahkan penyusupan ideologi komunis di tubuhnya.
Konflik ideologi dan dinamika politik menjadi landasan kuat bagi terjadinya tragedi ini. PKI, sebagai kekuatan politik yang tumbuh pesat, kerap bersinggungan dengan institusi militer. Ketegangan antara ideologi komunis dan nilai Pancasila, serta persaingan pengaruh kekuasaan, memunculkan kondisi rawan. Situasi semakin genting ketika PKI mencoba memperluas jaringan hingga ke dalam tubuh militer, melakukan propaganda, dan menggalang massa untuk mendukung ambisinya.
PKI, pada masa itu, telah tumbuh menjadi kekuatan politik signifikan. Dalam Pemilu 1955, partai ini meraih persentase suara yang besar dan menjadi salah satu kekuatan utama dalam percaturan politik. Keaktifan PKI dalam mobilisasi massa, propaganda, dan kritik terhadap militer maupun pemerintah menimbulkan ketegangan serius. Partai ini sering mengkritik militer dan pejabat yang menuduhnya sebagai birokrat korup, kapitalis, atau anti-komunis.
Saat hubungan antara PKI dan militer semakin meruncing, Presiden Soekarno justru semakin dekat dengan PKI. Pembubaran partai-partai oposisi seperti Masyumi dan PSI melemahkan lawan politik PKI, sementara ide “Nasakom” (Nasionalisme, Agama, Komunisme) oleh Soekarno memberi ruang lebih bagi PKI. Di masa itu, terjadi juga penolakan terhadap Manifesto Kebudayaan (Manikebu) oleh kelompok pro-komunis, serta konflik kebudayaan dan ideologi yang makin tajam.
Ketegangan memuncak ketika kondisi kesehatan Soekarno menurun, memunculkan kekhawatiran bahwa kepemimpinannya akan tergantikan. PKI melihat peluang untuk bergerak cepat. Dalam rapat internal pada akhir September 1965, PKI memutuskan bahwa langkah kudeta segera harus terjadi agar dapat mengamankan posisinya.
Isu Dewan Jenderal
Pada masa genting sekitar September 1965, beredar isu tentang adanya Dewan Jenderal yang terdiri atas sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka menyebut dewan jenderal tidak puas terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno dan berencana menggulingkannya.
PKI memunculkan isu Dewan Jenderal ini dengan menuduh beberapa jenderal TNI AD akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Lebih jauh, kudeta akan berlangsung bertepatan dengan hari angkatan bersenjata, 5 Oktober 1965.
G30S/PKI : Soerharto, Manipulasi dan Peran Asing
Dalam menghadapi tindakan G30S, militer — terutama oleh Panglima Kostrad saat itu, Soeharto — mengambil peran sentral dalam mengendalikan situasi. Pasukan militer berhasil membebaskan jenderal-jenderal yang tersandera dan merebut kembali gedung-gedung strategis di Jakarta. Setelah penguasaan kembali kota, operasi penumpasan terhadap kelompok pemicu, termasuk pembubaran struktur PKI dan penindakan terhadap orang-orang yang terafiliasi.
Dugaan Manipulasi Oleh Soeharto
Salah satu pertanyaan utama yang muncul: mengapa Soeharto, yang mengendalikan Kostrad pada saat itu, tidak menjadi sasaran dalam aksi penculikan? Padahal enam jenderal lain menjadi korban pembunuhan. Fakta ini memunculkan dugaan bahwa gerakan G30S bukan sekadar pemberontakan spontan, melainkan operasi rumit yang mungkin terkendali dari beberapa arah.
Setelah peristiwa tersebut, pemerintah Orde Baru segera mengambil alih narasi bahwa PKI adalah dalang utama. Melalui propaganda yang masif—dengan film, pendidikan, media massa— narasi PKI sebagai pengkhianat negara. Namun sejarawan menyebutkan narasi tersebut mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kompleksitas kejadian. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini oleh sebagian militer untuk memperkuat posisi mereka dalam politik.

Aktor Asing dan Intrik Politik Global
Dalam sudut pandang lain, G30S juga sebagai bagian dari konflik global antara blok Barat dan blok komunis. Beberapa pihak menduga keterlibatan intelijen asing dalam mempengaruhi arah peristiwa ini agar kepentingan negara-negara Barat terlindungi. Dokumen yang kemudian dideklasifikasi menunjukkan bahwa CIA dan badan intelijen Inggris pernah menaruh perhatian serius terhadap situasi Indonesia kala itu.
Dalam banyak riset, G30S/PKI sebagai “pretext” atau alasan untuk penumpasan massal terhadap mereka yang dianggap kiri. Buku-buku sejarah lebih kritis menyebut bahwa apa yang kemudian terjadi bukan hanya penegakan hukum terhadap pemberontakan, tetapi juga pengerahan kekerasan sistemik dan penghancuran terhadap lawan politik Soeharto.
Dampak Sosial dan Politik
G30S/PKI membawa konsekuensi luas bagi Indonesia. Salah satu dampak langsung adalah pembantaian dan pembersihan massal terhadap mereka yang dituduh berkaitan dengan PKI. Banyak orang ditangkap, dihukum, atau diasingkan tanpa proses hukum memadai. Dampak politik jangka panjangnya muncul dalam pergeseran kekuatan: militer mengambil posisi dominan dalam struktur pemerintahan, sementara pengaruh PKI dan partai komunis nyaris hilang dari ruang publik. Di ranah sosial, peristiwa ini menimbulkan luka mendalam, membekas di ingatan generasi bangsa. Rasa curiga, trauma, dan ketidakpercayaan antar kelompok menjadi bagian dari warisan sejarah agar tidak terulang.

Dampak G30S sangat dalam bagi Indonesia. Setelah kejadian, operasi penumpasan besar-besaran terhadap anggota PKI dan mereka yang punya afiliasi. Angka korban diperkirakan mencapai ratusan ribu, bahkan ada yang menyebut hingga satu juta jiwa. Pemenjaraan dan tindakan pengasingan tanpa proses hukum yang adil juga meluas.
Selama era Orde Baru, militer memperoleh posisi dominan dalam pemerintahan. Sebagian oposisi politik dibungkam. Komunis serta semua yang terkait dengannya mendapat stigma negatif hingga bertahun-tahun setelah Soeharto lengser. Trauma sosial, luka sejarah, dan ketidakpercayaan antar kelompok tetap menyertai perjalanan bangsa.
Tragedi 30 September 1965 mengajarkan kita pentingnya menjaga persatuan bangsa, toleransi, dan penyelesaian konflik melalui dialog, bukan kekerasan. Masyarakat diingatkan agar tidak membiarkan kebencian menjadi pemicu perpecahan. Memahami peristiwa ini secara kritis dan penuh empati menjadi langkah penting untuk menghormati para korban dan mencegah agar sejarah kelam tidak terulang kembali.
G30S/PKI bukanlah peristiwa hitam-putih. Di dalamnya terdapat elemen misteri, manipulasi sejarah, dan aktor tersembunyi. Meski banyak narasi telah dibentuk selama era Orde Baru, masih banyak celah yang menunggu penelitian lebih mendalam. Untuk generasi sekarang dan mendatang, penting mengkaji peristiwa ini secara objektif, kritis, dan menghormati korban serta keluarga mereka, agar tragedi serupa tidak terulang lagi.